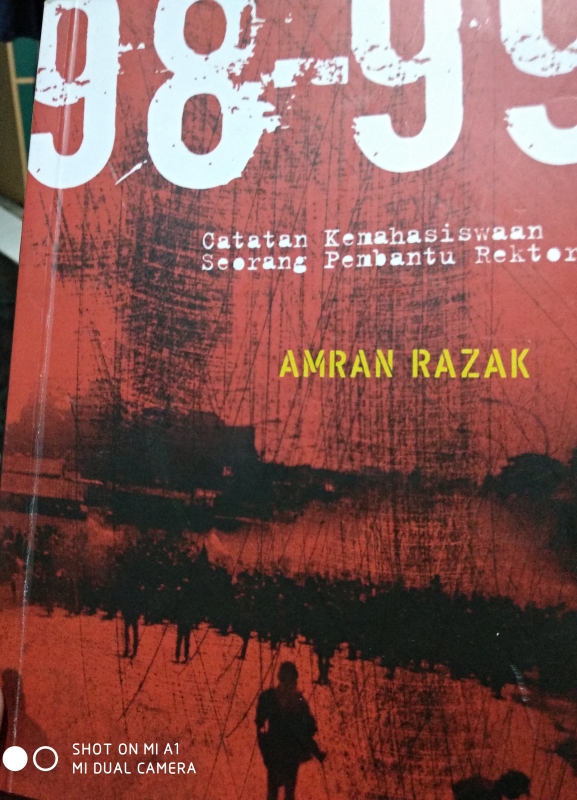Gray Work: Dilema Tersembunyi di Balik Produktivitas Modern
“The future of work isn’t about working more, it’s about working smarter. But first, we must uncover what’s hidden in the shadows.” – Reid Hoffman, pendiri LinkedIn
Di tengah hiruk-pikuk transformasi digital yang menyelimuti dunia kerja modern, sebuah fenomena baru tengah menggerogoti produktivitas tanpa disadari. Gray Work – atau “pekerjaan abu-abu” – hadir sebagai musuh tersembunyi yang mengintai di setiap sudut kantor virtual maupun fisik kita. Seperti bayangan yang mengikuti langkah, fenomena ini tumbuh subur dalam celah-celah sistem kerja yang tampak sempurna dari luar.
Bayangkan seorang karyawan yang menghabiskan tiga jam setiap paginya hanya untuk mengumpulkan data dari berbagai platform yang tidak terhubung. Atau seorang manajer yang terpaksa melakukan tugas manual berulang-ulang karena sistem otomatis tidak berfungsi dengan baik. Inilah wajah Gray Work – biaya tersembunyi dari data yang terputus dan solusi manual yang menghantui hampir setiap organisasi di era digital ini.
Akar masalah Gray Work terletak pada paradoks teknologi modern. Semakin banyak tools dan platform yang kita adopsi untuk meningkatkan efisiensi, semakin terfragmentasi pula alur kerja kita.
Penelitian terbaru mengungkap fakta mengejutkan: hampir tiga perempat karyawan menghabiskan lebih dari 20 jam per minggu untuk mencari informasi di berbagai teknologi yang terpisah, bukannya menjalankan tanggung jawab pekerjaan utama mereka. Ini bukan hanya tentang waktu yang terbuang, tetapi tentang energi kreatif dan semangat kerja yang terkikis hari demi hari.
“Gray work bisa diartikan sebagai kerjaan tambahan yang muncul karena data terpisah-pisah dan aplikasi yang tidak terhubung,” demikian tertulis dalam laporan Entrepreneur yang dikutip pada Rabu, 3 September 2025, sebagaimana dilansir dari Silanews.com.
“Akibatnya karyawan harus bolak-balik buka banyak sistem, menyalin data manual, atau mencari informasi yang tercecer. Inilah yang membuat produktivitas menurun,” sambungnya.
Menurut laporan Quickbase Gray Work Report pada tahun 2025, menunjukan keterlibatan lebih dari 2.000 pekerja penuh waktu dari berbagai level jabatan.

Hasilnya, 80 persen responden mengatakan perusahaan mereka menambah investasi pada aplikasi produktivitas. Tetapi, 59 persen mengaku bekerja justru terasa makin sulit.
“Sebanyak 73 persen pekerja menilai banyaknya aplikasi manajemen proyek membuat informasi sulit dibagi. Sementara 75 persen merasa data tidak bisa dilihat utuh di satu tempat,” ungkap laporan itu.
Penyebab utama Gray Work dapat ditelusuri dari tiga sumber fundamental. Pertama, proliferasi aplikasi dan platform yang tidak terintegrasi menciptakan silo-silo informasi yang memaksa karyawan menjadi “penghubung manual” antar sistem.
Kedua, proses otomatisasi yang tidak sempurna atau gagal sering kali membutuhkan intervensi manusia yang tidak terdokumentasi.
Ketiga, budaya organisasi yang belum sepenuhnya mengakui dan mengatasi pekerjaan “invisible” ini, sehingga terus berkembang tanpa pengawasan.
Dampak Gray Work terhadap dunia kerja jauh lebih dalam dari sekadar penurunan produktivitas. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan yang menggerus moral karyawan.
Ketika sebagian besar waktu kerja dihabiskan untuk aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah nyata, perasaan tidak bermakna dalam bekerja mulai muncul. Tidak mengherankan jika tingkat engagement karyawan global mengalami penurunan, dengan tingkat keterlibatan karyawan global menurun pada 2024, begitu pula dengan kesejahteraan karyawan.
Dari perspektif ekonomi, Gray Work menciptakan inefisiensi yang massif. Bayangkan jika 20 jam per minggu dari setiap karyawan terbuang untuk aktivitas yang seharusnya dapat diotomatisasi atau dihilangkan. Dalam skala organisasi dengan ribuan karyawan, kerugian ini dapat mencapai miliaran rupiah per tahun dalam bentuk opportunity cost dan penurunan inovasi.
Indonesia, sebagai ekonomi digital yang berkembang pesat, tidak luput dari fenomena ini. Konteks unik Indonesia dengan keragaman sistem, infrastruktur teknologi yang beragam, dan tingkat digital literacy yang bervariasi menciptakan tantangan tersendiri dalam menangani Gray Work.
Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang telah mengadopsi berbagai platform digital namun belum berhasil mengintegrasikannya secara optimal. Dari startup teknologi di Jakarta hingga perusahaan manufaktur di Surabaya, cerita serupa terdengar: karyawan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memindahkan data antar sistem, menunggu approval yang terjebak dalam workflow digital yang rumit, atau melakukan reconciliation manual karena sistem tidak dapat “berbicara” satu sama lain.
Mengatasi Gray Work membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan teknologi, proses, dan budaya. Langkah pertama adalah audit menyeluruh terhadap alur kerja eksisting untuk mengidentifikasi titik-titik di mana Gray Work berkembang. Ini bukan sekadar pemetaan teknologi, tetapi pemahaman mendalam tentang bagaimana karyawan benar-benar menjalankan tugas mereka sehari-hari.
Solusi teknologi harus fokus pada integrasi dan otomatisasi yang cerdas. Platform low-code dan no-code dapat membantu organisasi menciptakan koneksi antar sistem tanpa membutuhkan investasi IT yang besar. Artificial Intelligence dan Machine Learning dapat diterapkan untuk mengotomatisasi tugas-tugas repetitif yang selama ini menjadi sumber Gray Work, meskipun 39% karyawan masih enggan mengadopsi tools baru.
Namun teknologi saja tidak cukup. Perubahan budaya organisasi menjadi kunci utama. Leadership harus mengakui eksistensi Gray Work dan menciptakan safe space bagi karyawan untuk melaporkan inefficiency tanpa takut disalahkan. Sistem reward harus didesain ulang untuk menghargai efficiency gain, bukan hanya output volume.
Dari perspektif individual, karyawan perlu diberdayakan dengan skill untuk mengidentifikasi dan mengatasi Gray Work dalam lingkup mereka. Training digital literacy yang fokus pada optimasi workflow, penggunaan tools collaboration yang efektif, dan mindset continuous improvement menjadi investasi jangka panjang yang berharga.
Strategi jangka panjang mengatasi Gray Work membutuhkan komitmen dari seluruh ekosistem kerja. Vendor teknologi harus lebih fokus pada interoperability dan user experience.
Regulator perlu mempertimbangkan standardisasi yang memudahkan integrasi sistem. Institusi pendidikan harus mempersiapkan lulusan yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu berpikir sistemik dalam merancang workflow yang efisien.
Melihat fenomena Gray Work di Indonesia, saya melihat peluang transformasi yang luar biasa. Indonesia memiliki kelebihan dalam hal adaptabilitas dan kreativitas dalam mengatasi keterbatasan.
Jika kita dapat mengatasi Gray Work dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya dalam menciptakan ekosistem kerja digital yang benar-benar produktif.
Fenomena Gray Work mengajarkan kita bahwa progress teknologi tanpa desain yang matang justru dapat menciptakan masalah baru. Namun sekaligus mengingatkan bahwa dengan awareness dan action yang tepat, kita dapat menciptakan future of work yang benar-benar humanis – di mana teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya.
Kita berada di titik infleksi yang krusial. Pilihan yang kita buat hari ini dalam menangani Gray Work akan menentukan apakah teknologi akan membebaskan potensi manusia atau justru menjeratnya dalam rutinitas yang tidak bermakna.
Mari kita pilih jalan yang memungkinkan setiap individu memberikan kontribusi terbaik mereka, tanpa terjebak dalam labirin Gray Work yang menggerogoti semangat dan produktivitas.
“The best way to find out if you can trust somebody is to trust them. But first, you must trust yourself to see clearly what needs to be changed.” – Ernest Hemingway